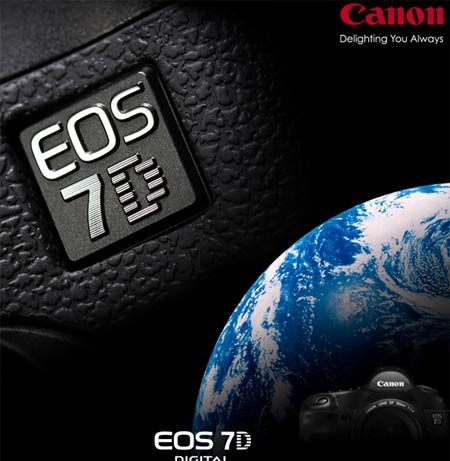Pameran Foto Bung Karno 2011: “Aku Melihat Indonesia”
Oleh Manshur Zikri / pada 20 Juni 2011 / di DKI Jakarta // 4 Komentar
Pinggangku mulai pegal karena sudah duduk lama di atas kursi kayu. Sebuah filem dokumenter tentang sejarah seorang pemimpin besar yang aku tonton waktu itu belum juga selesai sementara posisi duduk yang miring juga membuat leherku sakit. Posisi dudukku cukup dekat dengan layar TV, tetapi tidak berada pas di depannya melainkan sedikit di samping sehingga aku terpaksa duduk miring agar dapat melihat layar dengan jelas.

Pameran Foto Bung Karno
Tiba-tiba aku terkejut dengan sebuah tepukan di pundak oleh seseorang yang duduk di belakang. Dia kemudian tersenyum. Aku mengerti, bahwa posisi dudukku menghalangi pandangannya ke layar TV. Sekelabat melihat ke sekitar, ternyata kursi di sebelah orang itu kosong. Aku segera pindah ke sebelahnya, lalu lanjut menonton dengan sedikit rasa kesal karena kehilangan beberapa kalimat dalam pidato Presiden Republik Indonesia yang pertama itu saat peringatan hari ulang tahun Indonesia pada tahun 1959.

Layar TV yang menayangkan filem dokumenter tentang Bung Karno
Orang besar yang didampingi para ajudannya itu berdiri dengan gagah di atas mimbar, meneriakkan kata-kata revolusi dengan begitu semangat, menghipnotis semua orang yang menyaksikannya. Tepuk gemuruh rakyat yang hadir dalam upacara peringatan hari kemerdekaan berkali-kali diperlihatkan dan diperdengarkan dalam filem itu, meningkatkan rasa kerinduan pada seorang pemimpin yang disegani dunia pada masanya. Dialah Ir. Soekarno, Sang Proklamator, seorang tokoh yang tak seorang pun Warga Negara Indonesia yang tak mengenalnya. Walau hanya melalui sebuah tayangan filem dokumenter sejarah, arsip sejarah yang merupakan koleksi Arsip Nasional RI, keagungan kharismanya masih dapat dirasakan oleh diriku yang merupakan anak bumi manusia generasi sekarang.

Suasana di dalam gedung pameran
Merupakan suatu pengalaman yang menarik bagiku sendiri ketika menghadiri acara Pemeran Foto Bung Karno 2011, “Aku Melihat Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional Bulan Bung Karno 2011 dan DPP PDI Perjuangan, mulai dari tanggal 13 hingga 25 Juni 2011, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Hari itu, aku dan temanku, Ageung, datang pada Hari Minggu, tanggal 19 Juni.

Barisan foto dokumentasi perjuangan Soekarno yang dipajang di sepanjang dinding ruangan

Kutipan tulisan tangan Soekarno
Sebuah pameran yang bersifat terbuka tanpa pungutan biaya itu menjadi suatu kesempatan bagiku untuk melihat kembali sejarah perjalanan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan mengangkatnya menjadi salah satu negara yang diperhitungkan kekuatannya sebagai negara muda. Foto-foto dokumentasi Soekarno beserta keluarga dan kawan-kawan seperjuangannya dipajang di dinding-dinding gedung, disela dengan beberapa kutipan dari tulisan tangan Soekarno tentang pandangannya akan sebuah negara yang ideal dan usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama acara pameran, juga diputar filem-filem dokumenter yang memaparkan kronologi pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara, kisah perjalanan Soekarno mengelilingi dunia, dan rekaman-rekaman pidato Presiden pada berbagai event nasional maupun internasional.

Figur Soekarno
Pameran itu dirancang sedemikian rupa dengan dekoran kain-kain hitam yang menutupi beberapa dinding dalam ruangan, mungkin dengan maksud untuk meningkatkan rasa khidmad dalam mengenang kejayaan Soekarno sebagai tokoh perjuanngan. Salah satu ruangan juga diletakkan patung figuran wajah Soekarno, dari kepala hingga dada. Di ruangan itu para pengunjung mengambil gambar diri dengan berpose di sebelah patung, baik muda-mudi maupun bapak-ibu dan anak-anak. Sedangkan umbul-umbul yang mengibarkan wajah Soekarno dengan beberapa kata kutipannya dipajang sedemikian banyak di depan gedung pameran. Di samping pintu, dipasang sebuah baliho besar, tempat para pengunjung membubuhkan kesan dan pesannya tentang figur seorang Soekarno atau tentang acara pemerannya sendiri.

Antusiasme pengunjung ketika menonton filem dokumenter
Filem yang sedang aku tonton waktu itu adalah pidato Presiden pada peringatan HUT RI 14. Beberapa menit sebelumnya, aku telah menonton beberapa rekaman sejarah tentang kunjungan Soekarno ke negara lain, khususnya ke Amerika Serikat untuk memperkenalkan ideologi Bangsa Indonesia, Pancasila, di depan para pemimpin rakyat negara adidaya. Itulah waktu bagi Soekarno untuk membacakan lima prinsip dasar Negara Indonesia di hadapan dunia internasional, dan semua yang hadir dalam ruang pertemuan memberikan apresiasi tepuk tangan yang menggema. Aku bergetar dan merasa bangga menyaksikannya.
Aku rasa, bukan hanya aku yang bergetar ketika menyaksikan layar TV yang dipajang di ruangan depan gedung Galeri Cipta II itu. Ada banyak pengunjung yang datang menghadiri pameran, dari yang tua hingga yang muda. Pada waktu aku menonton pidato itu saja, sekitar pukul sebelas pagi, tempat duduk di depan TV dipenuhi orang-orang. Beruntung, kursi di sebelah orang yang menepuk pundakku itu kosong sehingga aku bisa pindah untuk mencari posisi yang lebih nyaman. Rata-rata anak muda yang datang ke pameran itu adalah remaja SMP dan SMA, dan mahasiswa. Ada juga anak-anak yang datang bersama keluarganya. Para orang tua tampaknya juga tidak bosan dengan kisah Soekarno, mereka ikut hadir di pameran, menonton dengan serius setiap episode filem dokumenter, berseru-seru dan berdecak kagum tentang tokoh pahalawan itu. “Itu Soekarno!” seru salah seorang kakek yang duduk di belakangku kepada cucunya. “Dia itu presiden pertama kita!” lanjutnya, sedangkan si cucu hanya mengangguk-angguk dengan ternganga, juga serius menonton filem.
Aku yang masih muda ini sangat mengagumi tokoh-tokoh pergerakan sejak jaman kolonial sampai era globalisasi. Mulai dari Cokroaminoto, Tan Malaka, Soe Hoek Gie, hingga kehebatan seorang Presiden Negara Chili yang berhasil menyelamatkan ratusan jiwa penambang yang terjebak di bawah tanah, Sebastian Pinera. Soekarno adalah salah satu sosok pemimpin yang menjadi idola para pemuda, pemuda masa silam dan pemuda jaman sekarang. Wajar saja beberapa kakek-nenek yang aku lihat ada di acara pameran hari itu masih sangat mengidolakan Si Bung Besar, karena mereka semua juga mengalami menjadi pemuda yang berapi-api pada masanya, terdorong bergerak maju karena kharisma seorang pemimpin.
“Mas, kalau bikin foto-foto itu gimana caranya, ya?” tanya si orang yang menepuk pundakku itu, lagi-lagi mengagetkanku yang baru saja asyik termenung dan sedari tadi terbuai dengan keanggunan Soekarno di dalam filem dokumenter yang sedang kami tonton. Aku melihatnya dengan bingung. Dia adalah seorang pemuda yang sedikit lebih tua dariku, memiliki tatapan mantap dan bersemangat. Pertanyaan itu menghantarkan aku ke sebuah percakapan yang aneh, yang tidak dapat aku ingat semua. Akan tetapi, kira-kira isi percakapan kami saat itu seperti ini:
“Foto apa, ya?” aku balik bertanya.
“Itu, foto-foto yang di sana!” katanya sambil menunjuk ke ruangan sebelah, tempat foto-foto dokumentasi Soekarno dipajang berderet pada dinding. “Kalau misalnya pakai kamera itu, supaya besar dan jelas begitu, bisa nggak, ya?”
Aku kemudian mengerti maksudnya, dan mengerti pula mengapa dia bertanya kepadaku, bukan kepada pemuda lain yang duduk di sebelah kirinya. “Oh, bisa, bisa!” jawabku.
“Itu modalnya berapa ya, Mas?”
“Itu tergantung kameranya, Mas. Kan keunggulan masing-masing kamera berbeda. Kalau dengan kamera ini, ya, standar, dan hasilnya juga biasa saja,” terangku sambil menunjukkan kamera yang sedari tadi aku bawa. Itulah alasan mengapa dia bertanya padaku.
“Tapi benar bisa kayak gitu? Yang ada di sana?” tanyanya lagi, kemudian membuka halaman-halaman dari sebuah buku yang sudah ada di hadapan kami sejak aku mulai duduk di sampingnya: sebuah buku lama yang sangat tebal, berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. “Ini, kan gambar ini sama semua dengan yang dipajang itu. Apa saya harus memfotonya dengan kamera, begini?” dia memperagakan seperti orang mengambil gambar dengan kamera.
Seketika aku teringat bahwa gambar-gambar yang dipajang itu tidak mungkin diambil dengan kamera foto, aku kemudian menjawab, “Oh, kalau yang di pameran ini bukan difoto, Mas. Tapi di-scan. Terus dicetak di kertas foto, dibuat jadi lebih besar.”
“Di-scan?” matanya mencerminkan kebingungan. “Oh, di-scan ya?” dia mengangguk-angguk. “Bukan dengan foto, Mas, ya?”
“Bukan. Kalau itu, mah pasti scan-an!” kataku meyakinkan.

Orang yang bertanya tentang foto (baju hitam)
Orang yang duduk di sebalahku itu sangat memancing tanya dalam kepala. Dari pertanyaannya, dari ekspresi kebingungannya tentang scan, dan juga dari penampilannya. Dia mengenakan pakaian hitam dari atas sampai bawah, seperti seragam seorang pelajar ilmu beladiri pencaksilat. Dan dalam percakapan-percakapanku selanjutnya, aku ketahui dia sedang berada di Medan beberapa waktu yang lalu, dan sengaja datang ke Jakarta untuk menghadiri acara Pameran Foto Bung Karno. Pemuda lain yang duduk di sebelah kirinya itu ternyata teman seperjalanannya. Dari logat bicaranya, aku menebak bahwa dia bukan orang Jakarta asli, tetapi dia tahu lebih banyak tentang Jakarta, terutama tentang penjual-penjual buku sejarah yang ada di Jakarta. Dia sempat menyebutkan sebuah tempat penjual buku bekas yang murah dan lengkap dengan koleksi buku sejarah langka (menurutnya), yang terletak di dekat jembatan di satu lokasi di Jakarta. Aku tidak ingat nama tempatnya, tetapi setelah aku pikir-pikir lagi, mungkin yang dia maksud adalah sebuah tempat penjual buku bekas di Jatinegara.

Buku “Di Bawah Bendera Revolusi”
“Buku ini saya dapat di sana,” katanya tentang buku yang ada di hadapan kami ketika aku mencoba membolak-balik halaman kusam dari buku itu. Buku yang tebal, penuh foto-foto yang sama persis dengan yang dipajang di pameran. Aku lihat di halaman pertamanya, buku itu terbitan tahun 60-an (aku juga lupa, berapa persisnya).
“Waktu saya tanya ke mas yang di sana,” lanjutnya sambil menunjuk ke arah penjual buku yang ada di belakang meja penyambut tamu. “katanya harga buku ini segini!” dia merentangkan ke sepuluh jarinya. Aku bingung, apakah maksudnya sepuluh ribu, seratus ribu, atau sepuluh juta? Aku tak hiraukan tebak-tebakan di dalam kepala, dan hanya berseru, “Oh, iya?!”
“Iya!” serunya. “Saya nggak bisa ditipu, dong! Ini aja saya dapat harganya cuma beberapa ratus ribu!”
Aku diam, tak terlalu menanggapi, karena lebih tertarik dengan buku tebal yang sedang aku lihat beberapa halamannya itu. Beberapa saat kemudian, orang itu bertanya lagi, “Mas emang suka yang begini-begini, ya?”
“Ng…?” aku bingung lagi dengan pertanyaannya, tetapi cepat menanggapi, “Oh, ya, saya datang, ya buat belajar aja, Mas.”
“Hm, tapi Mas udah pernah ke Medan?”
“Belum, belum, saya belum pernah ke Medan!” jawabku.
Percakapan kami berhenti, lalu kami lanjut menonton filem dokumenter. Ketika percakapan itu selesai, layar TV kembali menayangkan pidato Soekarno di hari kemerdekaan. Aku pikir aku sudah menonton semua filem dokumenternya sehingga meninggalkan tempat duduk dan menyusul temanku. Setelah puas mengamati semua isi pameran, aku mengusulkan untuk mencari makan, dan sekaligus langsung pulang ke kosan.

Orang-orang menuliskan pesan dan kesan di baliho yang terletak di sebelah pintu masuk gedung pameran

Seorang kakek menulis pesan dan kesannya di baliho
Namun, sebelum kami benar-benar beranjak dari gedung itu, aku dan Ageung tertarik dengan antusiasme beberapa orang yang menulis kesan dan pesan di baliho besar yang dipampang di sebelah kiri pintu masuk gedung. Aku pun terniat untuk membubuhkan tulisan di halaman itu. Dan sekali lagi, aku berhadapan dengan sesuatu yang menarik. Seorang kakek tua tiba-tiba menyalip diriku dan menulis di tempat yang ingin aku tulis. Karena merasa tidak enak jika melawan orang tua, aku mempersilakannya menulis lebih dulu. Aku dan Ageung tertarik untuk mengintip apa yang akan ia tulis. Tidak berbeda dengan tulisan-tulisan lain yang telah dibubuhkan di halaman baliho itu, si bapak itu menulis: “Bung Karno idola saya sepanjang masa, semoga amal dan perjuangannya diterima oleh Yang Maha Esa”, dengan tanda tangan bernama Chalijaani.
Awalnya aku menduga bahwa si kakek adalah orang biasa yang sedang bertamasya ke acara pameran di Hari Minggu, atau aktivis seniman yang sering berada di Taman Ismail Marzuki. Akan tetapi, coba tebak (dan ini yang menjadi menarik), bahwa ternyata si kakek itu adalah seorang penjual poster berwajah Bung Karno. Suatu profesi yang idealis, menurutku, karena dorongannya untuk berjualan bukanlah persoalan untung rugi, tetapi lebih kepada alasan kekagumannya pada sosok Soekarno. Dia menjajakan barang dagangannya sekitar beberapa meter di depan gedung galeri.

Kakek tua yang ternyata seorang penjual poster
“Saya ini sudah menjual poster Bung Karno sejak dulu, udah belasan tahun!” katanya tiba-tiba tanpa ditanya, ketika aku berniat membeli salah satu posternya. “Dulu saya nggak jualan di sini, tapi udah sejak dari Blitar! Di makam.”
“Di mana, Pak?” aku bertanya.
“Di Blitar, makamnya Bung Karno. Kalau Bu Fatmawati, kan di Karet!” terangnya. Kemudian dia melanjutkan, “Waktu itu ketemu Buk Mega, tahun 2004, saya juga jualan poster. Saya sudah dari dulu suka Bung Karno. Saya lihat langsung waktu dia pidato.”
“Oh, iya, Pak?” aku terkagum dengan ucapannya. “Yang di…”
“Itu Monas, kalau dulu Ikada!”
“Ya, maksud saya Ikada, Pak!” aku mengiyakan, padahal lokasi yang sebenarnya dari tempat terlaksananya rapat raksasa pasca proklamasi kemerdekaan itu adalah Lapangan Banteng yang terletak di dekat Katedral besar, yang letaknya memang di sekitar Tugu Monumen Nasional.
“Waktu itu saya masih muda,” lanjutnya. “umur…empat belas tahun, apa?”
“Sekarang umur Bapak berapa, Pak?” Ageung bertanya.
“Tujuh puluh tahun…” jawabnya. Sekali lagi aku bingung dalam percakapan yang kedua itu. Kalau misalnya umur si kakek memang 70 tahun, seharusnya dia berumur 4 tahun waktu rapat raksasa di Lapangan Ikada.
“Saya ambil poster yang ini aja deh, Pak!” kataku akhrinya setelah lama menimbang poster mana yang akan dibeli. Si kakek kemudian menggulung poster Soekarno harga Rp 5000,00 itu dengan karet gelang dan menyerahkannya padaku, seraya bertanya, “Tinggal di mana, Nak?”
“Kita tinggal di Lenteng, Pak!” jawabku. “Bapak dari hari pertama jualan di sini?”
“Nggak, baru dua hari ini. Biasanya, kan nggak jualan di sini,” terangnya.
Setelah membeli poster itu, aku dan Ageung berjalan pulang menuju Stasiun Kereta Cikini. Sebelumnya, kami menyempatkan diri makan ketoprak di pinggir jalan. Dalam perjalanan pulang itu, aku memberikan poster Bung Karno yang aku beli ke Ageung, karena bukan hobiku untuk mengoleksi poster. Anehnya, dan tidak tahu kenapa, saat kami makan, Ageung memberikan poster itu kepada si penjual ketoprak. Mungkin, karena dia sudah memiliki sebuah foto Soekarno segede gaban di rumahnya, di Sukabumi. Karena seingatku, ayahnya Ageung adalah seorang pengagum Soekarno. Abang penjual itu menerimanya dengan senang hati, tersenyum puas ketika melihat tampang Soekarno dalam poster, lalu menyimpannya dengan baik-baik di dalam rak gerobak.
Sambil makan ketoprak, aku mengingat lagi pengalaman di dalam gedung. Sebuah acara pemeran yang dimotori oleh tim atau panitia dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno itu terlihat seperti tidak melewati proses kuratorial, dan hanya sekedar memamerkan arsip-arsip sejarah sang tokoh. Menurutku pribadi, dekoran dalam gedung galeri yang dimaksudkan untuk meningkatkan romantisme dalam mengenang Soekarno belum terlalu mengena. Sungguh disayangkan, untuk tokoh sebesar Bung Karno, sajian acara untuk memperingati perjuangannya belum terancang secara maksimal. Namun demikian, terlepas dari kekurangan acara pameran, apresiasi perlu juga diberikan kepada penyelenggara. Karena kenyataannya, sajian pameran itu tidak menyurutkan semangat para pengunjung untuk mendatangi acara pameran, dan mereka juga dapat mencair ke dalam ruang-ruang dokumentasi kehidupan perjuangan sang pahlawan.

Soekarno adalah tokoh legenda, dan dia berjaya pada masanya. Pengalaman menghadiri acara pameran dan percakapan singkat dengan dua orang pengagum Soekarno menjadi pelajaran yang cukup berharga bagiku untuk mengenal sosok Soekarno dan bagaimana pandangan orang lain terhadapnya. Dia adalah aktor dahulu, tokoh pergerakan masa lampau. Sekarang ini, aku dan teman-teman sepantaranku yang lain memiliki tuntutan untuk meneruskan perjuangannya. Inilah waktu bagi kami untuk datang menghadapi tantangan-tantangan perubahan dunia yang terus berkembang menuju titik akhir yang tidak diketahui kapan tibanya, dan menyusulnya mejadi seseorang yang telah menyumbangkan seluruh hidupnya untuk negeri ini. Seperti tulisan yang aku bubuhkan di baliho, aku seolah berkata pada Bung Karno tentang peranku yang harus aku tuntaskan, “Ok, Big Bro! Here I come!”